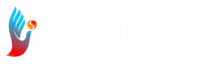Tembok GWK Runtuh oleh Palu Kebijakan dan Palu ‘Medsos’
Bali tak lagi hanya bergema dengan gemerincing gamelan, tapi juga dengan gemuruh protes di media sosial. “Tembok GWK” bukan lagi sekadar struktur beton, melainkan sebuah simbol eksklusivitas yang berhasil diangkat menjadi isu nasional oleh “parlemen medsos”—sebutan untuk kekuatan kolektif netizen yang mampu mempengaruhi kebijakan.
Aksi warga yang merasa haknya direnggut dengan dibangunnya tembok penghalang jalan, awalnya hanya menjadi keluhan lokal. Namun, kamera ponsel dan unggahan di platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter mengubahnya menjadi badai digital. Video warga yang harus memutar jauh, narasi tentang “Bali yang dikapitalisasi,” dan sindiran “main GTA di Ungasan” menciptakan tekanan yang tak terbendung.






Dalam situasi inilah, pemerintah tak bisa lagi berdiam. Pertemuan dramatis pada 30 September 2025 pukul 22.30 WITA antara Gubernur Wayan Koster, Bupati Badung, dan manajemen GWK adalah bentuk respons langsung dari tekanan “parlemen medsos” tersebut. Keputusan tegas untuk merobohkan tembok bukan hanya lahir dari meja rapat, tetapi dari gelombang ketidakpuasan publik yang dimagnifikasi oleh media sosial. Pemerintah, dalam hal ini, bertindak sebagai eksekutor yang mendengarkan suara rakyat yang telah diperkuat oleh platform digital.
Manajemen GWK yang akhirnya “ngangguk manis” dan berjanji membongkar tembok juga adalah bentuk adaptasi. Mereka menyadari bahwa dalam era digital, reputasi brand lebih berharga daripada sebidang tanah. Menentang “parlemen medsos” berarti mengundang krisis citra yang bisa berdampak finansial jangka panjang.
Kesimpulannya, “drama tembok” GWK adalah bukti nyata pergeseran kekuasaan. Kebijakan pemerintahan dan manajemen korporasi kini tak hanya ditentukan di ruang rapat, tetapi juga di ruang digital, di mana suara kolektif—jika cukup keras—dapat memaksa tembok mana pun untuk runtuh.