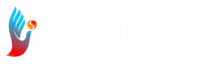Dalam panggung politik Indonesia, sosok Prabowo Subianto hadir sebagai figur yang sarat paradoks. Di balik retorika tentang kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, tersembunyi sebuah relasi kompleks yang kerap luput dari sorotan publik: hubungan psikologisnya dengan industri kelapa sawit. Sebuah analisis psikoanalisis terhadap perilaku dan kebijakannya mengungkap dinamika kejiwaan yang tidak hanya problematik, tetapi juga mengandung elemen-elemen yang dapat dikategorikan sebagai irasional bahkan self-defeating.
Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha besar di sektor perkebunan, telah menjadikan sawit bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari identitas politiknya. Sawit adalah simbol dari kekuatan ekonomi yang ia pegang, sekaligus representasi dari kuasa atas tanah dan sumber daya alam. Dalam kerangka psikoanalisis Freudian, hubungan ini dapat dibaca sebagai sublimasi—di mana dorongan-dorongan agresi dan hasrat untuk menguasai (yang kerap diasosiasikan dengan masa lalunya yang kontroversial) menemukan saluran yang ‘legal’ dan terhormat melalui penguasaan lahan sawit skala besar. Industri ini menjadi ruang di mana naluri untuk mendominasi dirayakan tanpa harus berhadapan langsung dengan kritik moral.
Namun, yang tampak sebagai strategi rasional justru mengandung logika yang idiotik. Kebijakannya yang mendorong ekspansi sawit seringkali mengabaikan realitas ekologis dan sosial yang paling mendasar. Ia seperti terjebak dalam apa yang dalam psikologi disebut sebagai ‘cognitive fixation’—pola pikir kaku di mana satu objek (dalam hal ini sawit) dianggap sebagai solusi untuk segala masalah, mulai dari devisa negara hingga kemiskinan. Pola pikir ini menutup pintu bagi alternatif lain yang mungkin lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Ini adalah bentuk reduksi realitas yang kompleks menjadi sebuah narasi tunggal yang simplistik, sebuah pelarian dari tanggung jawab untuk berpikir jernih dan holistik.
Di tingkat yang lebih dalam, terdapat mekanisme pertahanan ego yang kuat: disosiasi. Prabowo mampu berbicara tentang lingkungan dan kesejahteraan rakyat kecil di satu podium, sementara di sisi lain, kepentingan bisnisnya berkontribusi pada deforestasi dan konflik agraria yang justru merugikan kelompok tersebut. Pemisahan ini memungkinkannya untuk menghindari kecemasan (anxiety) yang akan muncul jika ia harus mengakui kontradiksi dalam dirinya sendiri. Perilaku ini bukanlah kebetulan, melainkan strategi ketidaksadaran untuk mempertahankan koherensi diri di tengah nilai-nilai yang saling bertubrukan.
Yang paling mengkhawatirkan adalah normalisasi dari pola pikir ini. Ketika logika ekspansi sawit yang merusak diangkat menjadi kebijakan nasional tanpa kritik mendalam, maka yang terjadi adalah institusionalisasi dari sebuah ‘kebodohan fungsional’—sebuah keadaan sistem dan publik terhadap konsekuensi jangka panjang yang destruktif demi keuntungan jangka pendek yang semu. Prabowo, dalam konteks ini, bukan hanya pelaku, tetapi juga simbol dari sebuah psikopatologi kolektif di mana kita memilih untuk tidak melihat dampak dari keserakahan yang kita rayakan.
Dengan demikian, relasi Prabowo dengan sawit lebih dari sekadar hubungan bisnis-politik yang transaksional. Ia adalah cermin dari konflik kejiwaan yang tidak terselesaikan, sebuah teatrikal di mana hasrat, penolakan, dan pelarian bermain dalam skala nasional. Dan kita semua, dengan diam, menjadi penonton sekaligus korban dari drama psikologis yang satu ini.