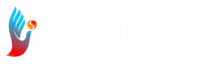Kriminalisasi Para Penjaga Bumi: Saat Aktivis WALHI Diringkus, Sementara Akar Masalah Deforestasi Diabaikan
[JAKARTA] – Dalam sebuah operasi yang dinilai banyak kalangan sebagai upaya kriminalisasi, dua aktivis lingkungan dari WALHI Jawa Tengah, Adetya ‘Dea’ Pramandira dan Fathul Munif, ditangkap atas dugaan penghalangan terhadap proyek yang mereka nilai merusak lingkungan. Penangkapan ini menciptakan ironi pahit: para pemuda yang berdiri di garda terdepan membela kedaulatan lingkungan justru dicap sebagai penjahat, sementara kebijakan masa lalu yang menjadi akar permasalahan deforestasi sistematis, seperti era Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014), luput dari pertanggungjawaban.Profil dan Sepak Terjang Dua Pembela Lingkungan
Adetya ‘Dea’ Pramandira bukanlah nama asing di dunia advokasi lingkungan Jawa Tengah. Perempuan lulusan Sosiologi ini telah lama menjadi ujung tombak pendampingan masyarakat yang ruang hidupnya terancam proyek-proyek ekstraktif dan pembangunan yang mengabaikan analisis dampak lingkungan (Amdal). Dea dikenal sebagai aktivis yang tekun melakukan pendokumentasian, pendidikan politik lingkungan kepada komunitas, dan membangun strategi gerakan. Perjuangannya bersentuhan langsung dengan konflik agraria dan lingkungan, membela petani dan nelayan kecil yang seringkali tak didengar suaranya.
Fathul Munif, rekan seperjuangan Dea di WALHI Jateng, adalah sosok yang banyak berkecimpung dalam riset dan kampanye berbasis data. Latar belakangnya memungkinkannya untuk membedah dokumen-dokumen perizinan, menganalisis kebijakan, dan menerjemahkan kompleksitas masalah lingkungan menjadi narasi yang mudah dipahami publik. Munif adalah penggerak di balik layar yang memastikan setiap advokasi didukung oleh pijakan data dan argumentasi hukum yang kuat.
Mereka berdua mewakili wajah gerakan lingkungan muda Indonesia: cerdas, militan, dan berkomitmen pada pembelaan terhadap alam dan masyarakat marginal. Kini, komitmen itu dibalas dengan jerat hukum.
Warisan Kebijakan Zulhas: Izin yang Menghancurkan Hutan Sumatera
Untuk memahami konteks yang lebih luas, kita harus menengok ke belakang, tepatnya pada periode kepemimpinan Zulkifli Hasan di Kementerian Kehutanan. Pada masa itu, terjadi percepatan dramatis dalam pelepasan kawasan hutan.
Data dari Greenomics Indonesia (2014) mencatat, pada periode 2009-2014, Zulhas menjadi menteri yang paling banyak menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, dengan total mencapai sekitar 1,6 juta hektare. Sebagian besar izin ini terkonsentrasi di Sumatera, yang merupakan rumah bagi hutan hujan tropis dan ekosistem gambut yang kritis.
Salah satu kasus yang mencuat dan mengaitkan Zulhas dengan praktik korupsi adalah pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014. Kala itu, KPK menyelidiki dugaan suap terkait revisi tata ruang dan alih fungsi hutan di Provinsi Riau, yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Kasus ini berpusat pada penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/Menhut-II/2014 tentang pelepasan kawasan hutan di Riau. Meski Zulhas memberikan klarifikasi dan membantah terlibat, SK yang ditandatanganinya itulah yang menjadi objek transaksi suap.
Banjir Pembalakan: Konsekuensi Nyata di Tengah Masyarakat
Kebijakan masif alih fungsi hutan ini bukan hanya angka di atas kertas. Ia memiliki wajah korban yang nyata. Masyarakat di berbagai wilayah Sumatera kini akrab dengan bencana tahunan: banjir bandang yang dalam istilah aktivis lingkungan disebut sebagai “banjir pembalakan”.
Hilangnya tutupan hutan akibat pembukaan perkebunan skala besar mengakibatkan daerah tangkapan air (catchment area) kritis. Data dari World Resources Institute (WRI) melalui platform Global Forest Watch menunjukkan, Provinsi Riau saja kehilangan puluhan ribu hektare tutupan hutan alamiah pada periode yang tumpang tindih dengan pasca-kebijakan Zulhas. Ketika hujan turun, tak ada lagi akar pepohonan yang menahan dan menyerap air. Air langsung meluncur deras dari dataran tinggi, membawa material lumpur dan menerjang permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur. Rakyat jelata, yang tidak pernah menikmati rente dari izin-izin mewah itu, yang akhirnya menanggung beban.
Kesimpulan: Mengalihkan Perhatian dari Akar Masalah
Penangkapan terhadap Adetya Pramandira dan Fathul Munif adalah sebuah distorsi prioritas penegakan hukum. Alih-alih menuntaskan akar korupsi di sektor kehutanan yang telah melahirkan kebijakan merusak dan memakan korban jiwa, aparat justru memidanakan para pengingatnya.
Ini adalah pola klasik: kriminalisasi terhadap pembela lingkungan. Dea dan Munif adalah simbol dari suara yang hendak dibungkam, sementara warisan kebijakan Zulhas dan para penerusnya yang terus membuka keran deforestasi, dibiarkan terus mengalirkan bencana bagi rakyat di Sumatera dan seluruh Indonesia. Pertanyaannya tetap menggantung: siapakah sebenarnya penjahat lingkungan yang sesungguhnya?